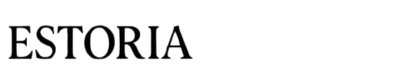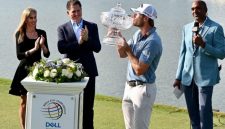“Satir itu doa yang disampaikan lewat tawa. Orang boleh marah, tapi semoga setelah tertawa, mereka lebih waras melihat dunia.”
“Kalau seni hanya membuat orang tertawa, ia berhenti di tawa. Tapi kalau seni bisa membuat orang tertawa lalu berpikir, di situlah seni menemukan martabatnya.”
— Butet Kartaredjasa
SOSOK, ESTORIA.ID – Di Yogyakarta, ada seorang anak yang tumbuh di tengah panggung, cat minyak, dan denting gamelan. Namanya Bambang Ekoloyo Butet Kartaredjasa, lahir pada 21 November 1961.
Ia putra dari maestro tari dan pelukis Bagong Kussudiardja, serta Soetiana, seorang ibu yang menyiapkan rumah agar tetap kokoh di tengah riuhnya dunia seni.
Butet tidak bisa memilih lahir dari rahim seni, tapi ia bisa memilih caranya menafsirkan seni itu sendiri. Jika Bagong menari dengan tubuhnya, Butet memilih melenturkan lidah.
Sejak remaja, Butet sudah terlibat dalam komunitas teater. Dari Teater Kita-Kita (1977), Sanggar Bambu (1978–1981), Teater Dinasti (1982–1985), hingga akhirnya berlabuh di Teater Gandrik (1985).
Teater Gandrik adalah sebuah kelompok teater satir yang lahir dari rahim mahasiswa dan budayawan Yogya. Di sini, ia menemukan medan yang tepat untuk menyalurkan bakat akting sekaligus kritik sosial.
Namun, yang membuat Butet berbeda bukan hanya aktingnya, melainkan keberaniannya mengubah humor menjadi senjata kritik.
Lidah yang (Tidak Pernah Benar-benar) Pingsan
Butet melejit lewat monolog berjudul Lidah Pingsan (1997). Pementasan ini ditulis oleh Agus Noor dan Indra Tranggono, dengan musik dari adiknya, Djaduk Ferianto.
Pentas digelar di Societet, Taman Budaya Yogyakarta, hanya beberapa bulan sebelum krisis moneter dan keruntuhan Orde Baru.
Tema yang diangkat sederhana, tapi menusuk: lidah, sebagai simbol komunikasi, kuasa, sekaligus pengkhianatan.
Monolog ini bicara tentang relasi antara media, politik, dan kebenaran di sebuah negeri yang tengah dilanda represi.
Dari panggung itu, Butet menemukan panggilannya: menjadi suara satir bagi publik yang lidahnya dipaksa diam.
Julukan “Raja Monolog” pun dilekatkan oleh Romo Mangunwijaya dalam sebuah catatan Kompas (1998).
Sejak itu, lahirlah serial monolog politik yang legendaris:
- Lidah (Masih) Pingsan (1998)
- Mayat Terhormat (2003)
- Matinya Toekang Kritik (2006)
- Presiden Guyonan (2008)
Di setiap pementasan, Butet tidak hanya menghibur. Ia menggelitik, menyentil, sekaligus menyampaikan kritik tajam tanpa kehilangan kelucuan.
Antara Sentilan, Sentilun, dan Republik Satir
Jika panggung teater memberi Butet audiens terbatas, televisi menghadirkan panggung yang lebih luas.
Program Sentilan–Sentilun, kemudian berkembang menjadi Republik Sentilan Sentilun di Metro TV, menjadi ikon satir politik Indonesia 2000-an.
Formatnya sederhana: dua tokoh dialog. Ndoro Sentilan (Slamet Rahardjo) dan Sentilun (Butet). Keduanya berdebat soal isu politik aktual.
Dengan gaya Jawa alus bercampur ceplas-ceplos, Butet tampil sebagai “wong cilik” yang mempertanyakan absurditas kekuasaan.
Tayangan ini kemudian menjadi ruang belajar politik publik di tengah minimnya literasi politik pascareformasi.
Tidak heran, banyak penonton menganggap Butet sebagai “oposisi yang selalu tersenyum.”
Buku, Kolom, dan Presiden Guyonan
Pada 2008, Butet menerbitkan buku Presiden Guyonan, kumpulan sketsa sosial dari kolom mingguan yang ia tulis. Buku itu diluncurkan bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-47.
Uniknya, Butet menyerahkan buku tersebut secara simbolik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono; sebuah gestur satir yang mempertemukan “presiden asli” dengan “presiden guyonan.”
Buku itu menegaskan bahwa satir Butet tidak berhenti di panggung. Ia hadir di media cetak, mengisi kolom, dan terus berusaha menyalakan akal sehat publik.
Film dan Layar Lebar
Meski teater adalah rumah utamanya, Butet tidak asing dengan film. Ia mencatatkan diri dalam sejumlah produksi populer, seperti:
- Petualangan Sherina (2000) — sebagai Pak Raden
- Soegija (2012) — nominasi FFI Pemeran Pendukung Pria Terbaik
- Jailangkung (2017)
- Abracadabra (2020)
- Gatotkaca: Satria Dewa (2022)
Kehadirannya di layar lebar menegaskan fleksibilitasnya sebagai aktor: bisa serius, bisa komikal, tapi selalu otentik.
Warisan Padepokan
Sebagai putra Bagong, Butet memikul tanggung jawab menjaga Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK).
Padepokan ini merupakan ruang seni, ekosistem tempat seniman muda berkarya lintas disiplin.
Dalam beberapa tahun terakhir, PSBK mengalami revitalisasi. Pada 2024, kawasan PSBK diresmikan kembali dengan wajah baru, sebuah arsitektur karya Eko Prawoto, dukungan Kementerian PUPR, serta semangat keberlanjutan seni.
Butet, yang duduk sebagai Ketua/Dewan Pembina Yayasan, memastikan tempat ini tetap hidup sebagai “rumah bersama” seniman.
Warisan Bagong diteruskan bukan dengan meniru, melainkan dengan memperluas.
Humor sebagai Kritik Serius
Banyak yang menyebut Butet “pelawak.” Ia menolak label itu. Baginya, ia adalah aktor yang menggunakan humor sebagai metode.
“Kalau pelawak sekadar membuat orang tertawa, aku ingin orang tertawa lalu berpikir,” ujarnya dalam berbagai kesempatan.
Strateginya sederhana tapi tajam:
- Impersonasi (menirukan suara Soeharto, gaya pejabat)
- Dialog kontras (Ndoro Sentilan vs Sentilun)
- Bahasa plesetan (menggunakan peribahasa Jawa atau sindiran lokal)
Di tangan Butet, humor tidak pernah kosong. Ia selalu membawa “sting”, sengatan kecil yang mengingatkan publik bahwa demokrasi butuh kewaspadaan.
Antara Panggung dan Politik
Dalam perjalanan kariernya, Butet kerap menuai risiko. Puisinya, monolognya, atau sekadar pantun di sebuah forum bisa memantik polemik. Namun ia tidak mundur.
“Kalau seni hanya untuk menghibur, ia berhenti di tawa. Kalau seni untuk mengingatkan, ia bisa menyalakan kesadaran,” begitu kira-kira prinsip Butet.
Maka tidak heran, ia kerap diundang bukan hanya ke panggung seni, tetapi juga forum politik, konferensi kebudayaan, bahkan diskusi akademik lintas negara.
“Indonesia Kita” Panggung Kebinekaan
Sejak 2011, bersama Agus Noor dan Djaduk Ferianto, Butet menggagas program teater populer “Indonesia Kita”.
Pertunjukan ini rutin digelar di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, dengan format drama musikal komedi yang mengangkat isu kebinekaan dan persatuan.
Lewat “Indonesia Kita”, Butet membuktikan bahwa panggung bisa menjadi ruang edukasi kebangsaan yang tetap menghibur.
Jejak, Warisan, dan Relevansi
Kini, di usia lebih dari enam dekade, Butet Kartaredjasa tetap aktif. Rambutnya memang memutih, tapi lidahnya tidak pernah pingsan.
Dari Gandrik hingga Metro TV, dari PSBK hingga panggung Indonesia Kita, Butet mewakili sebuah tradisi satir Indonesia.
Ketika humor menjadi jalan paling aman dan paling cerdas untuk bicara serius tentang bangsa.
Ia bukan politisi, tapi pidatonya didengar. Ia bukan akademisi, tapi gagasannya ditelaah. Ia bukan komedian semata, tapi tanpa humornya, publik bisa kehilangan cara untuk menertawakan kekuasaan yang berlebihan.
Butet adalah contoh bahwa dalam demokrasi, tertawa bisa menjadi bentuk perlawanan paling elegan.
Butet Kartaredjasa lebih dari sekadar “raja monolog.” Ia adalah penjaga lidah bangsa, yang memastikan bahwa kata-kata tidak dibungkam, melainkan terus mengalir. Kadang getir, sering lucu, tapi selalu menyentuh inti.
Di tengah zaman ketika kritik sering dianggap ancaman, Butet membuktikan, bahwa tertawa adalah jalan menuju kewarasan. ***
Penulis : Mazdon
Editor : Amin Bashiri