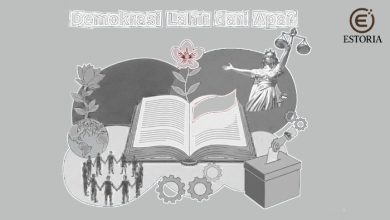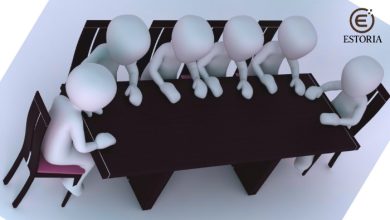Kapan Kita Jadi Warga?
Pepatah bilang, "Rumah membentuk kita, negara menguji kita". Apa maksudnya? Sejak kapan, dan di mana sebenarnya, kesadaran sebagai warga negara itu lahir?

ESTORIA — Judul dan teaser pemantik di atas adalah pertanyaan teman saat ngopi di Warkop Brobaks, Senin (23/2/2026). Penulis jadi tertarik menjawabnya lewat catatan ini.
Kalau dipikir, benar bahwa padamulanya, kita lahir sebagai anak, lalu tumbuh sebagai anggota keluarga. Tetapi jarang ada yang sadar bahwa saat itu, sebenarnya kita sedang tidak otomatis menjadi warga negara.
Di Indonesia, banyak orang memahami peran domestiknya dengan baik. Patuh pada orang tua, menjaga nama keluarga, menghormati yang lebih tua, namun gagap ketika berbicara soal hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Maka wajar menurutku, jika tadi teman bertanya, kapan sebenarnya kita menjadi warga?
Secara hukum, status warga negara melekat sejak lahir dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun secara kesadaran politik, menjadi warga adalah proses.
Tentu, keasadaran itu tidak datang otomatis bersama akta kelahiran atau kartu identitas. Ia tumbuh dari pemahaman tentang hak, tanggung jawab, dan keberanian berpartisipasi di ruang publik.
Di dalam keluarga, kita belajar struktur otoritas. Ada yang memimpin, ada yang mengikuti. Pola ini sering kali terbawa ke kehidupan bernegara.
Jika sejak kecil kita dibiasakan untuk tidak bertanya, tidak berbeda pendapat, dan sekadar patuh, maka ketika dewasa, kita cenderung memandang negara dengan cara yang sama. Sesuatu yang tak boleh dikritik.
Padahal, negara bukan orang tua. Negara adalah sistem yang dijalankan oleh lembaga dan pejabat publik. Ada eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, ada legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat, dan ada lembaga yudikatif yang menguji konstitusionalitas kebijakan, termasuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Semua bekerja dalam kerangka hukum yang bisa diawasi, dikritisi, bahkan diuji.
Menjadi warga, berarti memahami bahwa suara kita memiliki nilai. Hak memilih dalam pemilu, menyampaikan pendapat, hingga mengawasi kebijakan publik bukanlah gangguan terhadap stabilitas, melainkan fondasi demokrasi.
Reformasi politik sejak Reformasi 1998 membuka ruang partisipasi yang lebih luas, tetapi ruang itu tak akan berarti tanpa kesadaran.
Masalahnya, pendidikan kewargaan sering berhenti pada hafalan pasal dan simbol. Kita tahu lambang negara, tetapi tidak selalu paham fungsi kontrol sosial. Kita hafal sila-sila, tetapi belum tentu berani mengkritik kebijakan yang tak adil.
Di sinilah barangkali, transisi dari “anak” ke “warga” menjadi penting. Jika keluarga adalah ruang belajar nilai, maka negara adalah ruang ujian nilai.
Di rumah kita diajarkan tanggung jawab, di ruang publik kita mempraktikkannya. Di rumah kita belajar tentang keadilan versi kecil, di negara kita menuntut keadilan dalam skala besar.
Menjadi warga bukan soal usia, melainkan kesadaran. Ia lahir ketika kita mulai bertanya: kebijakan ini untuk siapa? anggaran ini dipakai untuk apa? suara saya berarti atau tidak?
Ya, dari rumah ke negara, perjalanan itu adalah perpindahan ruang. Perjalanan itu berupa perubahan cara berpikir, dari patuh tanpa tanya, menjadi partisipatif dan kritis. Dan mungkin, di sanalah demokrasi benar-benar dimulai.
***